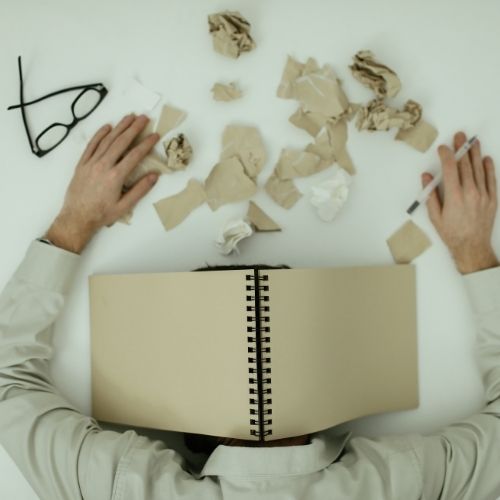Ketika Lelah Tidak Dianggap Serius
Rina, seorang staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, baru saja pulang kerja pukul sembilan malam untuk ketiga kalinya minggu ini. Ia mulai kehilangan fokus, sering melupakan hal-hal kecil, dan merasa kosong bahkan saat akhir pekan tiba. Namun ketika ia mengeluh, tanggapan yang ia dapat hanyalah, “Namanya juga kerja, ya capek wajar.” Padahal rasa capek itu bukan sekadar fisik—ia sudah merasa jenuh, putus asa, dan tidak bergairah menjalani hari-hari.
Kondisi seperti Rina tidaklah langka. Banyak orang di sekitar kita yang mengalami kelelahan luar biasa, tapi memilih diam karena takut dicap ‘kurang kuat’, ‘manja’, atau ‘tidak profesional’. Burnout bukan hanya istilah psikologi—ia adalah kenyataan sehari-hari yang tak terlihat, dan sayangnya sering diabaikan. Ini bukan tentang tidak mau bekerja keras, tapi tentang terus-menerus memaksa diri hingga tidak lagi merasa utuh sebagai manusia.
Mengapa ada kecenderungan masyarakat untuk meremehkan burnout? Apa yang membuatnya dianggap sebagai kelemahan, bukan sinyal untuk menata ulang sistem kerja dan hidup kita?
Budaya Kerja yang Memuliakan Ketahanan Ekstrem
Salah satu akar masalah terletak pada cara kita menilai produktivitas dan nilai diri. Dalam banyak lingkungan kerja, terutama di perkotaan, jam kerja panjang sering dianggap sebagai bukti dedikasi. Mereka yang pulang ‘terlalu cepat’ kadang dipandang tidak cukup berkontribusi, bahkan malas. Narasi seperti “kerja keras pasti berhasil” mengabaikan fakta bahwa tubuh dan pikiran punya batas.
Fenomena hustle culture turut memperkuat pandangan ini. Di media sosial, kita sering melihat glorifikasi kerja tanpa henti: bangun subuh, lembur hingga tengah malam, dan selalu ‘on’ setiap waktu. Mereka yang tidak sanggup mengikuti ritme ini, dianggap kalah sebelum bertanding. Padahal, tidak semua orang memiliki sumber daya fisik, psikis, dan sosial yang sama untuk menanggung beban tersebut.
Di sisi lain, banyak perusahaan masih belum memiliki sistem pendukung psikologis yang kuat. Misalnya, cuti sakit yang hanya berlaku untuk kondisi fisik, tidak mencakup kelelahan mental. Konseling kerja dianggap sebagai beban biaya, bukan investasi jangka panjang. Lingkungan kerja seperti ini memperkuat anggapan bahwa burnout adalah kelemahan pribadi, bukan gejala sistemik.
Mengapa Kita Takut Mengaku Burnout?
Ada ketakutan mendalam bahwa jika kita mengakui sedang burnout, reputasi kita akan jatuh. Seorang karyawan bisa merasa takut dianggap tidak sanggup memegang tanggung jawab atau tidak cocok dalam tim. Dalam dunia yang serba kompetitif, “rapuh” adalah label yang mengintimidasi. Padahal, setiap orang—tak peduli seberapa kompeten—punya titik lelah.
Di keluarga atau lingkungan sosial, burnout juga sering tidak dikenali. Ketika seseorang murung, cepat marah, atau menarik diri, ia malah dikritik atau disuruh “lebih bersyukur”. Respon-respon seperti ini membuat seseorang terisolasi, menumpuk tekanan internal, dan pada akhirnya justru bisa jatuh dalam depresi atau krisis identitas. Rasa malu menjadi penghalang utama untuk meminta bantuan.
Alih-alih diberi ruang, banyak orang malah merasa perlu membungkam sinyal tubuh dan emosi mereka demi terlihat ‘normal’. Padahal dengan terus berpura-pura kuat, kita sedang menggali lubang kelelahan yang lebih dalam.
Dampak Burnout yang Lebih Luas dari Sekadar Kinerja
Burnout tidak hanya merusak produktivitas seseorang di tempat kerja. Ia juga memengaruhi cara seseorang menjalani hidup secara keseluruhan. Hubungan dengan keluarga menjadi renggang, hobi dan minat yang dulu memberi semangat kini ditinggalkan, bahkan kemampuan mengambil keputusan pun menurun drastis. Efek psikologis seperti kehilangan makna hidup, insomnia, dan gangguan kecemasan bisa menyertai dalam jangka panjang.
Lebih jauh lagi, burnout berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat produktif. Jika ini terus dibiarkan, organisasi pun merugi: karyawan keluar masuk, semangat kerja rendah, hingga kesalahan kerja yang fatal. Pada skala nasional, burnout yang tidak tertangani menurunkan kualitas SDM dan daya saing global.
Inilah mengapa penting bagi kita untuk berhenti menganggap burnout sebagai persoalan individu. Ia adalah persoalan sosial, yang butuh perhatian kolektif—baik dari perusahaan, negara, maupun komunitas terkecil seperti keluarga.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Langkah pertama adalah mengubah cara berpikir. Kita perlu menerima bahwa burnout adalah kondisi nyata dan valid, bukan cermin kelemahan. Ini bisa dimulai dengan menyediakan ruang aman untuk bicara tanpa takut dihakimi baik di kantor maupun rumah. Organisasi harus proaktif membuat kebijakan yang melindungi kesehatan mental, seperti sistem kerja fleksibel, evaluasi beban kerja, hingga fasilitas konseling.
Individu pun perlu belajar membaca sinyal tubuh. Istirahat bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa memperluas pemahaman tentang burnout lewat literasi, diskusi, dan saling berbagi pengalaman. Cara paling mendasar adalah belajar berkata tidak, dan tidak merasa bersalah atas itu.
Kita perlu membangun narasi baru: bahwa mengakui burnout bukanlah tanda menyerah, tapi keberanian untuk memilih cara hidup yang lebih manusiawi. Karena hidup tidak hanya tentang bekerja tanpa henti, tapi juga tentang bertumbuh dengan utuh.
Burnout bukan tentang lemah, tapi tentang sistem yang sudah tidak lagi sehat. Menyalahkan individu hanya akan memperparah masalah. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk membuka mata, memahami, dan mengubah cara kita melihat kerja, produktivitas, dan nilai manusia.
Kalau kamu pernah merasa sendirian menghadapi kelelahan yang tak bisa dijelaskan, mungkin ini saatnya berhenti diam