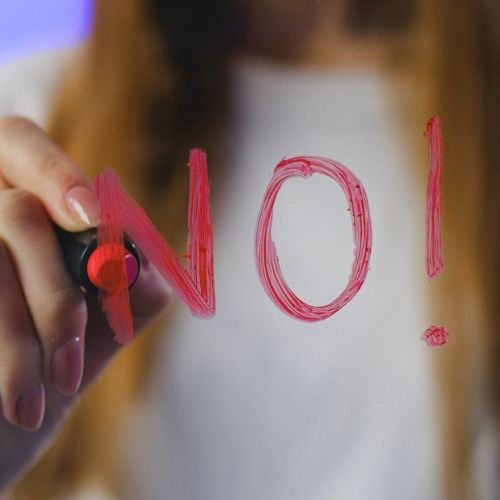Bayangkan kamu adalah Dita, lulusan baru dari universitas negeri ternama. IPK-nya nyaris sempurna, ia aktif di organisasi, dan pernah menjadi ketua panitia seminar nasional. Tapi setelah melamar lebih dari dua puluh perusahaan, tak satu pun yang memberikan panggilan kerja. Alasannya sama: belum punya pengalaman kerja.
Situasi ini bukan hanya dialami Dita. Banyak fresh graduate lain yang menghadapi pintu-pintu tertutup meski sudah berusaha keras membangun CV mereka. Di media sosial, mereka membaca tips sukses karier, tapi kenyataan yang dihadapi justru pahit dan membingungkan.
Ada pula Raka, lulusan politeknik, yang sejak SMA sudah membantu bisnis keluarganya. Ia menguasai akuntansi dan terbiasa mengelola stok barang. Namun, saat melamar kerja formal, semua pengalaman itu dianggap tidak relevan. Akhirnya, ia merasa tidak cukup layak meski kenyataannya ia sudah cukup teruji di dunia nyata.
Mengapa Pengalaman Jadi Syarat Padahal Baru Lulus?
Pertanyaan ini sering muncul: “Kalau semua perusahaan minta pengalaman, lalu siapa yang akan memberi kesempatan pertama?” Masalahnya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada sistem rekrutmen dan pendidikan yang berjalan di dua jalur berbeda. Di kampus, mahasiswa diajarkan teori dan idealisme. Di dunia kerja, yang dicari adalah efisiensi dan kesiapan praktik.
Syarat “pengalaman kerja” sering dijadikan filter awal oleh HR untuk menyaring pelamar dalam jumlah besar. Padahal, pengalaman itu tidak selalu menunjukkan kualitas atau kesesuaian karakter seseorang dengan budaya kerja. Sayangnya, sistem seleksi cenderung mengabaikan potensi tersembunyi dari lulusan baru.
Selain itu, beberapa perusahaan juga lebih memilih “aman”. Mereka menghindari risiko melatih seseorang dari nol karena membutuhkan waktu dan biaya. Akhirnya, mereka lebih memilih kandidat dengan rekam jejak—sekecil apa pun itu—daripada mereka yang benar-benar baru memulai. Inilah salah satu ironi dalam proses transisi pendidikan ke pekerjaan: mereka yang ingin belajar tidak diberi ruang untuk belajar.
Lebih dari Sekadar Kompetensi
Salah satu penyebab mendasar adalah kurangnya jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan tidak dibekali skill praktis yang dibutuhkan pasar kerja. Akibatnya, mereka terlihat “tidak siap”, meskipun sebenarnya mampu jika diberi waktu dan pelatihan. Kampus sibuk mengejar akreditasi, sementara dunia kerja mengejar target dan profit.
Ditambah lagi, sistem magang di banyak institusi masih bersifat simbolis. Mahasiswa menjalani magang hanya untuk menggugurkan syarat SKS, bukan untuk benar-benar belajar. Di sisi lain, perusahaan juga belum sepenuhnya menjadikan magang sebagai bagian dari talent pipeline jangka panjang. Ini menciptakan jurang yang melelahkan antara kelulusan dan pekerjaan pertama.
Tak bisa dipungkiri, privilege juga ikut bermain. Mereka yang punya akses ke lingkungan kerja profesional—lewat orang tua, kenalan, atau relasi organisasi—sering kali mendapat kesempatan lebih dulu. Sementara mereka yang berasal dari latar belakang biasa-biasa saja harus berjuang sendiri, tanpa peta dan tanpa koneksi. Ini bukan hanya soal skill, tapi juga soal siapa yang kamu kenal.
Dampak Psikologis dan Sosial yang Jarang Diperbincangkan
Ditolak berulang kali membuat banyak fresh graduate merasa tidak berharga. Mereka mulai mempertanyakan nilai diri, bahkan merasa bersalah karena tidak “cepat sukses” seperti ekspektasi sosial. Media sosial memperparah luka itu—feed Instagram dipenuhi pencapaian orang lain, sementara diri sendiri masih terjebak di tahap awal.
Lebih buruk lagi, tekanan dari keluarga dan lingkungan membuat mereka enggan bercerita. Banyak yang memilih diam karena tidak ingin dianggap sebagai beban. Padahal, mereka hanya butuh waktu dan kesempatan. Rasa malu tumbuh diam-diam, menggerogoti semangat hidup dan membunuh rasa percaya diri.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem dan kehilangan motivasi untuk berusaha. Beberapa memilih menyerah pada pekerjaan apa saja, bahkan yang jauh dari bidangnya, demi terlihat “produktif”. Akibatnya, potensi individu yang seharusnya bisa tumbuh optimal justru terhambat sejak awal.
Mulai dari Hal Kecil, Bukan Harapan Besar
Solusi tidak harus datang dari perusahaan besar atau kebijakan negara. Kadang, langkah kecil seperti membuka peluang magang berbayar atau program pelatihan kerja di komunitas lokal bisa menjadi awal yang penting. Fresh graduate juga bisa membangun pengalaman lewat proyek mandiri, volunteer, atau kursus online dengan portofolio nyata.
Kampus dan institusi pendidikan perlu berbenah. Mereka harus mulai menjalin kemitraan nyata dengan dunia industri, bukan hanya ceremonial. Mahasiswa perlu diberi ruang mencoba, gagal, dan tumbuh, bahkan sejak di bangku kuliah. Begitu juga dengan perusahaan, perlu ada perubahan mindset: memberi kesempatan bukanlah kerugian, tapi investasi.
Kita pun, sebagai sesama masyarakat, bisa membantu. Mulai dari mendengarkan cerita mereka, tidak buru-buru menghakimi, hingga memberi akses informasi kerja yang relevan. Jika kita ingin dunia kerja lebih adil dan inklusif, maka kita semua harus ambil bagian. Karena tidak semua orang punya suara dan sebagian memilih diam hanya karena dunia tidak memberinya tempat.
Kamu pernah mengalami hal serupa? Pernah merasa gagal hanya karena tak diberi kesempatan? Bagikan ceritamu di komentar. Siapa tahu, pengalamanmu bisa membantu seseorang yang sedang berjuang dalam diam.